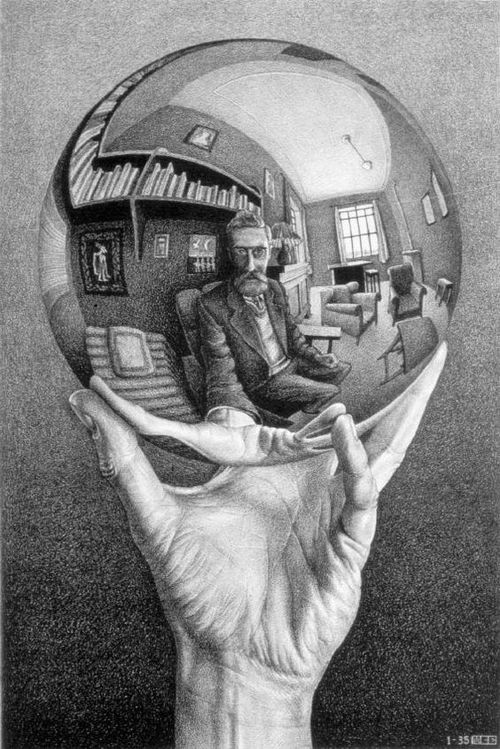Senin, Januari 2016
Semalam saya memimpikan mantan kekasih saya mati bersimbah darah di kamar kosnya. Berita berita nasional mengangkatnya sebagai headline karena dia mati bersimbah darah, perut terkoyak-koyak, dada rompal, bola matanya hilang sebelah, dan sebelah tangan dan kakinya hampir putus. Pembunuhan macam itu hanya bisa dilakukan oleh hewan buas atau gergaji mesin. Ternyata memang ada hewan buas di kamar kos mantan kekasih saya itu. Seseorang telah mengirimkan harimau kelaparan ke dalam kamarnya. Kemudian polisi menciduk saya karena diduga saya lah pelaku tunggal. Saya lah pemilik harimau kelaparan itu. Tangan saya diikat ke belakang dan saya diborgol. Harimau itu sudah mati pula. Mungkin karena makan makanan busuk. Ya, tubuh mantan kekasih saya itu. Akhirnya harimau saya mati. Dan saya dibawa ke jeruji besi. Saya kemudian terbangun dengan perasaan sedih. Karena mantan kekasih saya mati dan itu hanya mimpi. Tapi ada pula rasa senang kalau itu hanya mimpi. Artinya, saya tidak jadi dipenjara. Kemudian timbul lagi rasa sedih. Karena itu artinya saya tidak pernah memelihara hewan buas.
Selasa, Januari 2016
Saya berdiri di atas peron jalur dua Stasiun Tanah Abang. Keramaian membludak. Banyak sekali orang-orang. Kenapa orang-orang itu banyak sekali? Seperti jumlah laron yang mati terinjak-injak di lantai warung bakso di gang sebelah. Bagaimana bila manusia itu seperti laron di warung bakso itu? Diinjak-injak, mati, dan gepeng begitu saja. Dan dunia ini, hanya warung bakso di sebuah gang.
“Woi awas!” teriak petugas kereta api gara-gara banyak orang nyebrang ketika kereta mau lewat. Kadang saya berpikir beruntungnya bukan saya yang jadi petugas kereta itu. Karena kalau saya, mungkin sudah saya biarkan mereka itu. Saya biarkan dan menunggu tragedi apa yang akan terjadi siang hari ini. Kereta menubruk gerombolan dan gerombolan itu seperti laron di lantai warung bakso. Saya cuma berharap tidak ada sanak keluarga dan kerabat dalam gerombolan yang menyebrang itu.
Rabu, Januari 2016
Hari ini sialnya saya ketemu teman lama saya waktu sekolah dulu. Dia semakin cerewet hingga beruang mati di kutub utara pun dia bicarakan. Sekarang dia sudah mapan. Punya rumah di real estate, mobil fortuner, kolam renang, motor Harley, dan hewan buas di belakang rumahnya. Saya tidak terkejut apalagi iri. Toh, dari dulu sekolah kan bapaknya sudah ketahuan korupsi, nah kalau sekarang beliau itu sudah bebas dan bisa bangun kekayaan lagi. Oh iya, dia cerita juga kalau punya tanah dimana-mana jadi sekarang dia bisa ongkang-ongkang kaki, pakai kolor doang, dan jalan-jalan ke mall sama istri dan anak-anak tercinta. Dia ceritakan itu seakan-akan dia orang paling bahagia di dunia. Lah kok bisa? Terus dia sesumbar begini “Saya amal banyak, ke mana-mana, jadi saya yakin tidak bakal melarat. Nggak mungkin banget deh. Kau tertarik nggak tanam saham di perusahaan saya?” dia nanya begitu. Saya cuma senyum terus pamit pulang. Jabat tangan, tersenyum, sembari berkelakar “Boleh nanti kalau kamu bangkrut!” dia tertawa saja.
Di jalan pulang ke rumah saya membayangkan kalau teman saya yang kaya itu tiba-tiba tersangkut kasus penipuan atau korupsi dan jadi buronan polisi. Anak istri ditelantarkan, diintrogasi polisi. Hidup tidak tenang. Perusahaan kanan kiri bangkrut. Relasi habis dan malah menusuk dari belakang. Dan terakhir jadi melarat. Roda hidup itu berputar, bung! Dan biarkan roda itu melindas kau punya cangkem!
Kamis, Januari 2016
Pulang liputan dari Pelmerah, saya langsung nulis berita. Tengah malam begini baru sempat merenung-renung. Lewat pasar palmerah tadi ada belasan tandan pisang dibungkus-bungkus koran kayak mayat dikafani. Iseng lah saya berpikir, bagaimana kalau di dalam itu ternyata orang? Dan penjual itu merupakan pembunuh bayaran yang berkedok penjual pisang? Dan di salah satu bungkusan itu ternyata ada mayat (bukan) teman saya yang cerewet atau mantan kekasih saya? Atau muka muka koruptor? Atau muka bos saya yang licik? Ah sudah lah, pikiran begini kalau dibiarkan muncul, nanti saya bisa mimpi mantan saya mati berdarah-darah kayak Senin lalu.
Jumat, Januari 2016
Pagi ini saya sudah dibuat kesal oleh ribuan pendemo yang turun ke jalan. Jalanan mampat. Macet di mana-mana. Bangsat! Saya ada liputan pagi-pagi sama orang penting. Akhirnya saya parkir mobil di pinggir jalan dan jalan kaki bareng pendemo itu. Orang-orang banyak kayak gula pasir tumpah di dapur. Lagi jalan itu, saya membayangkan, bagaimana bila salah satu dari mereka ada teroris yang meledakkan diri di tengah kerumunan massa? Mereka akan terpental dan darah di mana-mana. Persis kayak laron mati yang diinjak-injak di lantai warung bakso gang sebelah. Tiba-tiba saya hanya ingin berjalan cepat-cepat. Dan dari kejauhan itu saya ingin dengar suara ledakan. Tapi sampai di lokasi janjian dengan orang penting itu, tidak ada suara apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Saya kecewa. Kekecewaan itu bertambah tatkala saya bertemu teman lama saya. Pekan yang payah.
Dia cerita kalau dia baru menikah tiga bulan lalu. Minta maaf karena tidak mengundang saya. Lupa katanya. Bagus deh, saya tidak perlu melihat dua orang bahagia di atas panggung cengar-cengir. Saya juga tidak perlu mendengar dia bercerita tentang pengalamannya menikah, sebenarnya. Tapi dia ngomong mulu kayak laron. Muka dia merah sambil sungging senyum lebar. Cerita kalau bininya enak, penurut, cantik, semok, bohay, kalau udah di ranjang, ‘beuuuhh…’ Saya mau bilang kalau saya tidak perlu mendengar anda bercerita tetapi tidak enak, kan namanya teman, jadi saya cuma bilang begini, “Wah, gue nggak sabar nunggu cerita lo tiga tahun lagi.”
Saya cuma pengen dia tahu kalau waktu itu bisa mengubah apa pun. Dan pejabat sialan itu baru datang satu jam kemudian. Wajar kalau korupsi duit, waktu aja dibuang-buang!
Sabtu, Januari 2016
Pulang liputan sengaja saya mampir foodcourt di mall. Lagi pengen saja, tiba-tiba kangen sama mbak-mbak yang jual dimsum, entah pertanda apa. Ya sudah saya beli dimsum satu porsi seharga Rp11.000 yang saya bayar pakai uang Rp100.000, dia tanya, “Mas ada duit pas nggak?” katanya ketus. “Wah enggak ada mbak,” “Yah. Yaudah bentar kembaliannya” kata dia lagi dengan muka ketusnya. Terus dia kembali ke kios dan nyari duit buat kembalian duit saya sambil masih masang muka asemnya itu. Saya pingin tertawa kok ya ndak enak. Jadi ini alasan saya kangen mbak-mbak dimsum? Mungkin karena kebanyakan berpikiran jahat, jadi saya kena batunya. Sekeliling saya ramai orang memadu kasih. Saya lupa kalau ini Malam Minggu. Waduh, kampret tenan! Saya buru-buru habiskan dimsum dan pulang. Di sekeliling foodcourt itu sepasang kekasih jumlahnya ngalahin korban bunuh diri di Arab Saudi, kayaknya. Banyak banget. Ada yang gandengan, ada yang rangkulan, ada yang makan sambil diem-dieman, ada yang ngobrol cekakak-cekikik, ada yang mau gumoh. Ya, yang mau gumoh itu saya. Sudah tau enek, saya malah makin jadi melihat sepasang sepasang itu satu per satu. Lihat muka ceweknya, lihat muka cowoknya sambil bergumam, “Halah, paling besok udah nggak gandengan. Halah paling besok putus. Halah itu lihat aja muka ceweknya minta putus gitu. Haduh mbak, nggak ngeliat itu cowoknya bosen? Lho, lho mbak lihat tuh cowoknya matanya kemana-mana! Aduh goblok banget, udah ketahuan itu cewekmu cuma mau morotin doang!”
Minggu, Januari 2016
Libur. Libur. Libur. Libur dari berpikiran jahat. Namaste dulu sama kopi, buku, musik. Kopinya kapal api, bukunya Charles Bukowski, musiknya Leonard Cohen lagi putar lagu Bird On The Wire. Nikmat mana lagi yang kau dustai wahai pengeluh ulung? Tiba-tiba saya mulai menyelami hari-hari kemarin. Banyak pikiran-pikiran jahat terlintas begitu saja tanpa dimau ataupun dimau. Tiba-tiba saya kepikiran Ratih, pegawai marketing baru yang punya senyum ayu biyanget! Saat mikirin Ratih itulah, sepenggal lirik ini muncul begitu saja seperti pikiran jahat lainnya:
“If I, if I have been unkind
I hope that you can just let it go by
If I, if I have been untrue
I hope you know it was never to you.”
Sebuah pesan buat jodoh saya kelak.
Depok, 12 Februari 2017